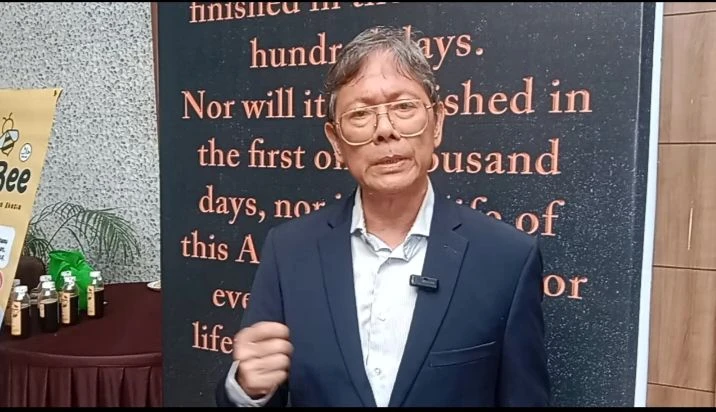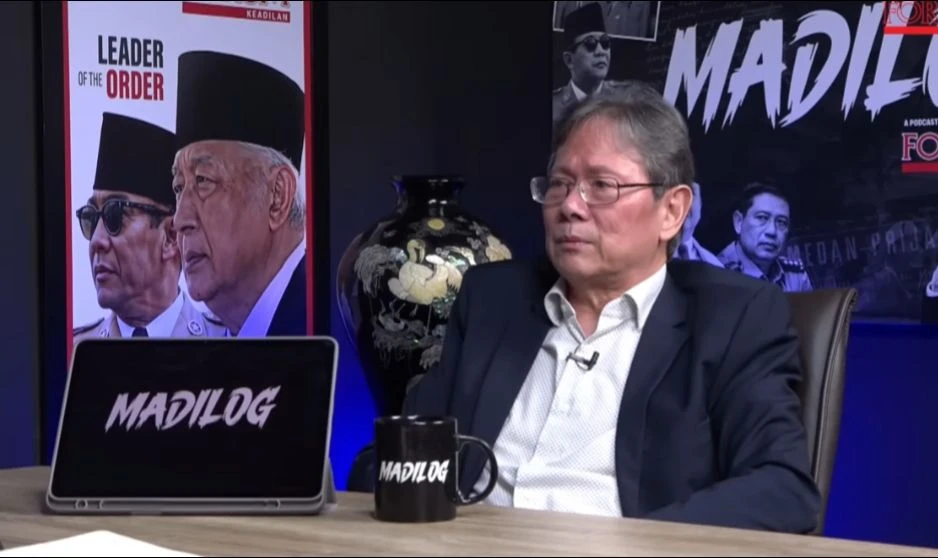NARASI RESMI tentang rasio utang dan defisit terdengar meyakinkan - tetapi kenyataannya penerimaan negara menyusut, beban bunga utang meningkat, dan institusi melemah di bawah tekanan politik.
---------------------------
Oleh: Dipo Satria Ramli
Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mantan direktur Macquarie Capital Indonesia dan penulis buku Ekonomi All-in
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan konferensi pers perdana “APBN Kita” dengan tenang: Defisit APBN hingga Agustus 2025 hanya Rp 322 triliun (US$19 miliar), atau 1,4 persen dari produk domestik bruto (PDB), masih jauh di bawah batas 3 persen.
Angka ini memancarkan pesan klasik yang sering ditunjukkan pejabat Indonesia: disiplin fiskal terjaga, aturan konstitusional dihormati, dan manajemen ekonomi tetap di jalur yang benar. Namun, di balik permukaan, angka-angka itu menutupi kenyataan yang lebih gelap.
Pendapatan negara hingga Agustus hanya mencapai Rp 1,64 kuadriliun, atau 57 persen dari target tahunan, turun 7,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Hampir semua sumber penerimaan negara menyusut: penerimaan pajak menurun, penerimaan migas melemah. Sementara itu, belanja negara terus naik, dan siklus utang pemerintah semakin bergantung pada pinjaman untuk membayar utang lama — utang hari ini membayar beban masa lalu, sekaligus mewariskan utang baru di masa depan.
Di balik proyeksi pertumbuhan PDB 5,0–5,2 persen, ada sinyal peringatan: rasio pajak terhadap PDB Indonesia merosot ke titik terendah dalam puluhan tahun.
Angka paling mengkhawatirkan ada di RAPBN 2026: Hampir 77 persen penerimaan pembiayaan baru bukan untuk sekolah, pabrik, atau infrastruktur, tetapi hanya untuk membayar bunga utang lama. Ini bukan lagi kebijakan fiskal yang sehat, melainkan spiral berbahaya: pinjaman hari ini untuk menambal defisit kemarin, sekaligus menyiapkan defisit esok hari.
Setiap putaran siklus ini memperdalam jebakan fiskal, menggerus ruang investasi produktif. Empat pilar kerentanan yang pernah dirumuskan Dana Moneter Internasional (IMF) pasca krisis Asia — posisi fiskal negara, guncangan eksternal, keberlanjutan utang, serta kelemahan institusional — kini makin nyata di Indonesia.
Jika diterapkan ke kondisi fiskal Indonesia sekarang, kerangka itu bukan hanya menandai risiko kesehatan keuangan negara, tetapi juga menunjukkan negara sedang menyusun arsitektur krisis berikutnya.
Pilar Pertama: Posisi Fiskal
Utang resmi pemerintah terlihat rapi, tetapi menutupi kewajiban besar di luar neraca: pinjaman BUMN, proyek dijamin negara, hingga kewajiban pensiun ASN yang pada akhirnya akan jatuh ke APBN saat masalah muncul.
Sejarah menunjukkan: penyelamatan Jiwasraya, Asabri, hingga Garuda Indonesia semua akhirnya dibiayai pajak rakyat. Tambahkan jaminan hukum proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serta kewajiban pensiun PNS, gambarnya jauh lebih suram.
Bahkan rasio defisit terhadap PDB yang dibanggakan di bawah 3 persen rapuh. Data BPS 2024 menunjukkan “statistik diskrepensi” sebesar Rp814 triliun—cukup besar untuk menggeser rasio fiskal beberapa poin desimal. Alih-alih konservatif, Indonesia diam-diam menumpuk kewajiban tersembunyi yang mempersempit ruang kebijakan.
Pilar Kedua: Sensitivitas terhadap Guncangan Eksternal
Indonesia sudah menunjukkan gejala rapuh. Pada kuartal II 2025, defisit transaksi berjalan melebar menjadi US$3 miliar (0,8 persen PDB) dan neraca pembayaran defisit US$6,7 miliar, dipicu arus keluar dividen/bunga serta dana asing dari pasar obligasi domestik. Utang luar negeri naik 6,1 persen yoy menjadi US$433,3 miliar.
Investor asing juga menjadi penjual bersih di 2025, melemahkan likuiditas pasar dan meningkatkan volatilitas.
Dibandingkan Thailand, Malaysia, dan Vietnam, ketergantungan Indonesia pada utang portofolio yang dipegang nonresiden membuatnya jauh lebih rentan ketika sentimen global berbalik. Dalam dunia perdagangan terfragmentasi dan tekanan keuangan meningkat, ketergantungan ini bisa memicu guncangan mendadak pada neraca pembayaran.
Pilar Ketiga: Retaknya Keberlanjutan Fiskal
Rasio pajak terhadap PDB semester I 2025 jatuh ke 8,42 persen (turun dari 9,49 persen setahun sebelumnya), salah satu yang terburuk dalam dekade. Ada jurang antara penerimaan dan kewajiban.
Hingga Agustus, penerimaan pajak baru 54,7 persen target dan turun 3,6 persen yoy. Namun pemerintah justru memperbesar komitmen: program makan bergizi gratis (MBG), intervensi koperasi Merah Putih (KMP), padahal basis penerimaan makin rapuh.
Jika tren ini berlanjut, defisit akan membengkak, bunga menggerus belanja pembangunan, dan negara kian mendekati implosi fiskal diam-diam.
Pilar Keempat: Runtuhnya Institusi
Bahaya terdalam bukan dari angka, melainkan pelapukan institusi.
Bank Indonesia, yang dulunya penjaga stabilitas moneter, kini terseret ke pembiayaan fiskal melalui skema “burden sharing”—membeli obligasi pemerintah dan menanggung bunga. Apa yang disebut “manajemen likuiditas” sejatinya adalah monetisasi defisit, merusak kredibilitas BI untuk menjaga rupiah dan mengetatkan kebijakan saat diperlukan.
Risiko meningkat ketika Purbaya menarik Rp200 triliun dari BI untuk ditempatkan di bank-bank negara, kemungkinan guna mendukung pinjaman koperasi dengan bunga 2 persen—jauh di bawah pasar. Langkah ini menguras likuiditas BI, melemahkan kemampuan stabilisasi rupiah, dan membuka risiko kredit bermotif politik, default, hingga bailout di masa depan.
Ketika aturan fiskal menjadi opsional dan independensi moneter terkikis, pasar tak akan ramah. Risiko krisis makin nyata.
Penutup
Keempat pilar ini melukiskan gambaran muram: penerimaan menyusut, utang membayar utang lama alih-alih pertumbuhan, dan institusi yang seharusnya menjaga stabilitas malah dibengkokkan oleh tekanan politik. Di atas kertas, rasio utang masih di bawah 40 persen PDB dan defisit dalam batas hukum, tetapi setiap siklus APBN mempersempit ruang fiskal, melemahkan independensi bank sentral, dan memperbesar risiko guncangan berikutnya.
Indonesia pernah melewati ini: ketika pasar kehilangan kepercayaan, pukulannya tiba-tiba dan brutal. Pertanyaannya kini bukan apakah retakan ada, melainkan berapa lama sebelum kepercayaan runtuh dan Indonesia dipaksa menghadapi krisis berikutnya.(*)